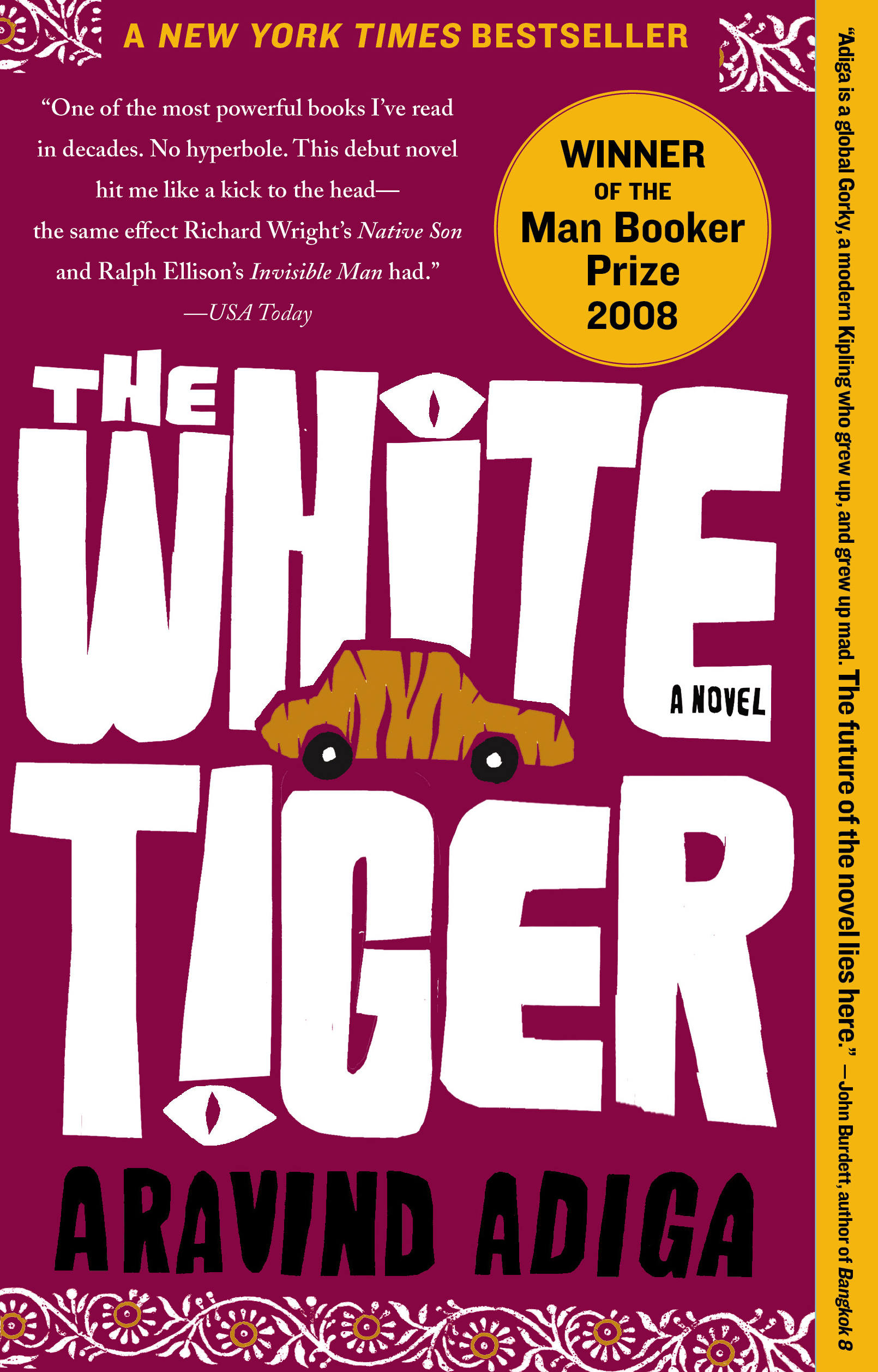
Saya menemukan The White Tiger karya Aravind Adiga saat tengah berkelana di Big Bad Wolf Fair, Mei lalu. Aduh. Hari itu rasanya saya ngebolang ke BSD seperti transit ke galaksi lain. Di galaksi itu, ada tempat parkir sedih yang terlantar di tengah-tengah ketiadaan, BUKU IMPOR DIJUAL 45 REBU, orang belanja buku pake kereta dorong abis sejuta, poster John Cena segede dosa dijual 170.000 (ada yang beli pula), dan orang kaya belanja sushi di Aeon seperti ibu saya belanja nugget buat sarapan.
Kebetulan (alhamdulilah) hari itu saya hanya membawa uang sekadarnya. Selain The White Tiger, saya hanya membeli Lord of the Flies dan Americanah. Semuanya 160.000. 160.000 bagi tiga tuh kira-kira 50 ribuan. Anjir. Gak nyesel juga sih, karena seandainya saya bawa duit banyak ujung-ujungnya bakal laper mata gak berfaedah. Satu-satunya penyesalan hanya karena belum sempat menelisik bagian nonfiksi. Teman-teman saya banyak yang dapat coffee table book kece yang biasanya gopean, hanya seharga seratus ribu.
Intinya, di pesta buku ini, sulit untuk mencari buku yang Anda inginkan secara spesifik. Ngana udah dikasih murah masih aja banyak tingkah. Tapi, justru itu cara terbaik untuk menemui buku kesukaanmu selanjutnya. Beda rasanya dengan membaca review di internet lalu memburu buku tertentu yang sudah pasti sesuai harapan. Saya suka berpura-pura takdir mempertemukan diri saya dengan buku acak yang akhirnya saya bawa pulang. Begitulah rasanya. Selain Americanah dan Lord of the Flies yang memang saya incar dari dulu, saya tak tahu buku mana yang harus saya beli untuk menunaikan slot ketiga. Saya ingin sesuatu yang baru, namun semua yang baru tampak terlalu asing. Akhirnya, saya memilih The White Tiger karena menurut sampulnya, si penulis memenangkan Man Booker Prize tahun 2008. Siapa tahu ketemu penulis yang senada Eka Kurniawan.
You ask ‘Are you a man or a demon?’ Neither, I say. I have woken up, and the rest of you are sleeping, and that is the only difference between us.
Buku ini memang terasa asing pada awalnya. Sinopsisnya aneh pula: kisah sukses seorang supir yang kemudian menjadi enterpreneur, anjir, kayak Merry Riana? Tapi, baiklah–begitu membuka halaman pertama, saya langsung terisap. Tutur kata Balram Halwai tak urung mengingatkan saya kepada suara sudut pandang pertama di novel Salman Rushdie dan Andrea Hirata. Cerita mengucur begitu saja, dengan kesederhanaan tokoh utama yang berasal dari keluarga miskin di sisi gelap negaranya. Tetapi si Balram ini selalu terdengar sotoy; ingin meyakinkan pembaca bahwa ia orang penting, revolusioner, dan Apa Yang Terjadi Selanjutnya Akan Mengejutkan Anda! Senada dengan suara Ikal dan Saleem Sinai. Mungkin paralel dengan protagonis tetralogi Laskar Pelangi ini yang membuat saya merasa terikat dengan buku tersebut, mengingat Laskar Pelangi adalah salah satu novel ((berat)) pertama yang pernah saya baca.
Hal lain yang membuat buku ini terasa akrab adalah penggambaran India yang sedikit mencerminkan Indonesia. India diceritakan tanpa pretensi di sini, dari mulut seseorang yang miskin, berasal dari kasta rendahan, dan putus sekolah. Dalam cerita, sebuah partai sosialis sedang berkuasa dalam waktu yang lama (!!!). Mereka terus memenangkan pemilu, padahal suara rakyat sudah tak berlaku lagi karena di desa-desa penduduk tak dapat kesempatan untuk memilih. Layanan masyarakat tak berlaku karena semuanya dijadiin duit sama pemerintah. Lagi-lagi, rakyat kecil menjadi korban di tengah permainan orang-orang besar. Terdengar akrab? Oh ya, ada juga adegan macet yang entah kenapa bikin saya girang banget karena deskripsinya berwarna sekali dan sama banget kayak yang di Thamrin.
Namun, tema utama buku ini adalah penjajahan yang dilakukan masyarakat kelas atas India terhadap bangsanya sendiri, atau yang disebut Balram sebagai teori Kandang Ayam. Menurut beliau, orang miskin di India kebanyakan menjadi pembantu yang seumur hidup sudah terdidik untuk manut perintah majikannya. Itulah mengapa tingkat kejahatan yang dilakukan pembantu di India rendah. Seorang majikan bisa memercayakan sejumlah besar uang kepada supirnya, dan mengharapkan uangnya kembali utuh. Tak ada yang berani memberontak. Mirip dengan kebudayaan Jawa yang katanya nrimo. Apakah Balram akan menjadi orang pertama yang akan memutuskan untuk keluar dari kandang miliknya?
Tidak salah buku ini mendapat penghargaan Man Booker Prize karena kekejamannya. Ada interview menarik dengan Aravind Adiga yang mengupas alasannya menulis buku ini, meskipun ia hidup sebagai orang India kelas atas, dan bagaimana buku ini membuatnya dikecam di negaranya sendiri.
Ini bukan buku berat. Semuanya diceritakan dengan gaya khas humor India yang menertawakan penderitaan mereka. Satu poin keakraban lagi, mirip dengan humor khas orang Jawa. Adiga adalah pencerita yang piawai. Ia pandai menarik-ulur ceritanya, diawali dengan tempo ringan-ringan bahagia, tapi bagian kedua ceritanya berbalik arah jadi thriller psikologis grim-dark penuh kegilaan yang bikin merinding. Seperti harimau putih yang menurut legenda India hanya muncul sekali dalam satu generasi, The White Tiger adalah potret kejujuran langka yang harus dirayakan.